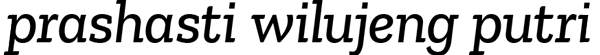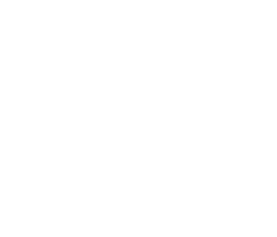Tulisan ini dimuat dalam sudji.id pada 2021 dengan judul yang sama. Tulisan ini adalah hasil penjelajahan riset candi-candi Jawa yang dilakukan oleh Candikala.id. Proyek seni ini dapat dilihat di Instagram Candikala.id
1. Tubuhku
Aku memeluk yasti (puncak bangunan stupa), andesit serupa tiang gemuk; lebar dan pendek. Sambil memeluk, aku berusaha mengangkatnya. Ternyata, jangankan mengangkat, menggeser pun aku tak bisa. Aku sudah mencoba berbagai cara dan gaya. Dari posisi kedua tangan di bagian bawah yasti, satu tangan di atas dan satu tangan di bawah, mendorong sambil berjongkok, menarik sambil berdiri, sampai mencoba menggeser dengan kakiku. Tetap tidak bisa. Napasku terengah-engah. Matahari seperti menertawaiku yang berpeluh dibuatnya.
Saat itu, aku berada di antara reruntuhan candi perwara yang belum direkonstruksi sepenuhnya di kompleks Candi Sewu. Di kanan, kiri, depan, dan belakangku hanya terlihat reruntuhan yang sudah dikelompokkan. Sepertinya para arkeolog sudah mengidentifikasi batu-batu andesit itu dan menentukan di sebelah mana mereka harus diletakkan. Mungkin memang menyusun batu-batu yang berantakan itu menjadi satu bangunan yang sarat sejarah itu sulit, karena batu-batu andesit itu hanya diletakkan begitu saja, sepertinya tidak sesuai dengan urutan konstruksi bangunannya. Matahari yang masih condong di timur tapi sudah hampir ke atas kepala membuat dimensi reruntuhan itu bertambah dalam. Bayangan satu kelompok reruntuhan candi menimpa kelompok reruntuhan candi lainnya. Kemudian, ada bayangan yang lebih besar daripada bayangan reruntuhan candi-candi perwara itu. Di balik sekitar dua baris tumpukan batu yang belum direkonstruksi, terdapat candi utama yang masih berdiri megah. Akan tetapi, ia tidak terlihat begitu jelas dari tempatku memeluk yasti. Hanya terkadang saat aku memanjat yasti dengan menginjak bagian yang agak menjorok ke luar, candi utama itu baru terlihat.
Anehnya, walaupun candi-candi perwara itu masih berupa reruntuhan, mereka terlihat sangat megah, membuat aku menjadi sangat kecil. Aku yang memakai baju berwarna dominan biru terlihat kontras sekali dengan warna batu andesit yang hitam keabuan. Sepertinya dulu, di abad kedelapan masehi, batu-batu andesit itu diambil dari Kali Opak yang ada di dekat Candi Prambanan. Candi Prambanan sendiri terletak hanya delapan ratus meter dari Candi Sewu. Bayangkan, sudah berapa peristiwa dialami oleh Candi Sewu sejak ia dibuat pada abad kedelapan masehi! Pantas saja, banyak candi perwara yang runtuh, dan untuk memasangnya kembali, para arkeolog harus mempelajari betul-betul peristiwa berabad-abad yang lalu. Sementara aku, yang lahir pada awal 90-an, baru hanya mengalami peristiwa yang terjadi selama hampir tiga puluh tahun belakangan ini.
Aku yang sangat jauh lebih muda daripada candi ini seakan masuk ke dunia yang lain, berbeda dari duniaku sehari-hari. Seperti dunia game. Aku seakan menjelajahi dunia seperti dalam permainan Minecraft yang sering dimainkan keponakanku. Aku menjelajah dunia trimatra kotak-kotak, menemukan dan mengekstrak suatu temuan untuk membangun struktur bangunan. Mencoba seperti seorang arkeolog, aku mereka-reka arah mata angin dan dewa-dewa Lokapala yang menjaga penjuru angin tersebut. Dalam usaha mengerti tentang peradaban manusia di bumi Jawa ini, aku sempat bingung membedakan antara ajaran Hindu dan Buddha, terutama Buddha Mahayana. Rupanya memang dalam perjalanannya, ada aliran Buddha yang terpengaruh oleh ajaran Hindu, maka lahirlah Buddha Mahayana. Aku pikir, kebudayaan dalam sejarah hidup manusia rupanya adalah suatu kolase. Suatu hasil dari ekstraksi pertemuan, timpalan, benturan, dan gesekan antara suatu gambar atau teks dengan gambar dan teks yang lain.
2. Tubuh Arca Candi
Secara bentuk yang dapat dilihat di hari ini, Candi Sewu pun tampak seperti kolase. Apabila aku melihat kompleks Candi Sewu dengan segala reruntuhannya dari atas, balok-balok dan arca-arca saling bertumpuk, menempel, dan terfragmentasi. Yasti saja, yang seharusnya ada di tempat yang paling atas dalam sebuah bangunan candi, malah berada di bawah, di antara puing-puing candi; ini adalah satu kolase tersendiri.
Arca-arca ini dulunya diproduksi untuk ritual keagamaan dan penyembahan kepada dewa. Karena materialnya yang terbuat dari batu andesit, ia tetap bertahan sampai sekarang, walaupun sudah ada bagian yang rusak di sana-sini. Arca-arca yang menggambarkan manusia Jawa pada waktu itu dengan cukup naturalistik berubah menjadi bentuk yang abstrak. Arca-arca itu sudah tidak utuh, tubuhnya tidak sempurna. Ada yang alasannya karena terkikis waktu: mereka jadi berubah dan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih abstrak, seperti muka yang hilang, atau tangan yang terletak di bawah mulut. Ukiran-ukiran yang timbul dan cekung menyatu bagai kolase dengan batu dalam bentuknya yang paling alamiah, yang berbentuk tidak beraturan dan belum diukir. Ada pula yang ukirannya masih terlihat sangat jelas. Hanya saja, karena proses rekonstruksi candi belum selesai, bentuknya seperti puzzle yang belum selesai disusun.

Arca-arca ini tidak dapat lagi ditentukan identitasnya, apakah ia seorang dewa, apakah dia seorang rsi, atau apakah dia perempuan atau laki-laki. Kita lihat saja arca ini. Kepalanya sudah tidak ada, tangannya hanya separuh. Kakinya ada dua pasang, namun salah satu pahanya sudah tidak ada. Di tempat yang seharusnya ada kepala, malahan terdapat balok dengan ukiran. Di pinggirnya, ada sebuah balok batu yang tergeletak diagonal, entah seharusnya seperti apa. Di tengah-tengah tubuh, yang sepertinya harusnya adalah tempat paha dan pinggul, malahan terdapat balok yang kasar, yang tidak beraturan bentuknya. Kakinya pun berpijak di atas balok-balok yang disusun tidak beraturan, dan tampak tidak kuat. Seakan ia mau rubuh. Ia menjadi tubuh yang kasar dan tidak beraturan, dikikis angin dan hujan, digoncang gempa bumi. Ia menjadi tubuh tanpa identitas.
3. Kolase Zaman
Tubuh-tubuh tanpa identitas itu sedikit-banyak membingungkanku dalam mempelajari Candi Sewu. Yang aku tahu hanyalah Candi Sewu adalah candi Buddha. Akan tetapi, secara umum pun, tidak sekali dua kali aku bingung, dan merasa terusik dengan pemikiran dari agama-agama bumi ini. Salah satu pemikiran yang mengusikku adalah konsep ketuhanan yang dianut. Dewa-dewa mereka mempunyai çakti. Çakti, seperti Dewi Lakhsmi dan Dewi Durga dalam Hindu, atau Dewi Tara dalam Buddha seringkali dibahas di sekolah sebagai istri dewa. Ternyata, aku baru memahaminya bahwa ia adalah energi dari dewa tersebut, dan oleh karenanya çakti dan dewa yang bersangkutan adalah satu. Menarik buatku, karena itu menunjukkan karakteristik budaya yang waktu, ruang, dan identitasnya membaur, dan bahkan ide yang serba baur itu dapat mematerial ke dalam suatu bentuk, baik laki-laki, perempuan, maupun keduanya. Narasi ini mempertentangkan waktu, ruang, dan identitas sebagai sebuah realitas baru. Hal ini cukup mengaduk-aduk kepalaku yang sudah dibiasakan berpikir dengan cara logis. Buatku, ide akan dewa dan çakti-nya ini adalah sesuatu yang secara spiritual ada, namun ia tidak ada di logika berpikirku.
Memang terdapat jarak umur yang jauh sekali antara aku dan Candi Sewu. Candi Sewu dibuat pada abad kedelapan. Sedangkan aku lahir pada akhir abad kedua puluh. Di rentang waktu antara kelahiranku dan kelahiran Candi Sewu terdapat banyak sekali peristiwa, dan setiap peristiwa sedikit-banyak mempengaaruhi nasib candi tersebut. Setiap raja yang bertahta di Mataram Kuno (Jawa Tengah) pasti menyumbang sesuatu kepada bangunan keagamaan ini. Baik itu diperbaiki, atau ditambah, atau bahkan dirusak.
Perpindahan Mataram Kuno ke Jawa Timur disebabkan oleh hal-hal yang masih menjadi asumsi di kalangan para arkeolog. Akan tetapi, apapun sebabnya, itu mengakibatkan ditinggalkannya candi-candi di Jawa Tengah oleh penduduk di sana. Sehingga, saya pikir, Candi Sewu dibiarkan terbengkalai untuk beberapa waktu. Setelah Kerajaan Mataram Kuno mengalami pralaya (kiamat) akibat hal-hal seperti serangan kerajaan lain, pertempuran, ataupun bencana alam, entah apa yang terjadi pada Candi Sewu. Mungkin ia dibiarkan saja tanpa ada perawatan sedikit pun. Bisa juga, ia tertutup abu gunung Merapi yang meletus, atau mungkin juga tertutup pohon-pohon yang menjadi hutan sehingga orang-orang yang hidup di sana tidak mengetahui keberadaannya.
Candi Sewu pun mungkin menjadi saksi konflik yang terjadi pada Kerajaan Mataram Islam. Terletak di Jalan Raya Solo-Jogja KM 16, ia pasti menyaksikan konflik perebutan kekuasaan Solo dan Jogja, dengan campur tangan kumpeni (perusahaan dagang Veerenigde Oost Incische Compagnie, ata V.O.C.). Orang-orang Eropa yang gemar mengarsip apapun[1] membuat gambar berupa denah yang menunjukkan muka candi induk dan candi perwara. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa baik tentang si candi maupun tentang masyarakat yang mendiaminya mungkin saja melakukan banyak kesalahan saat melakukan pengarsipan. Mungkin, untuk mereka itu bukan kesalahan, karena mereka mengarsip sesuai dengan isi kepala mereka. Menurut catatan seorang Eropa yang lain, Candi Sewu mengalami kerusakan parah saat Perang Diponegoro karena batu-batunya dipergunakan oleh warga setempat untuk membuat benteng pertahanan. Ada juga yang mengambilnya untuk membuat rumah. Manjushrighra mengalami graha. Rumah suci (tempat pemujaan) mengalami kehancuran.
Setelah teknologi kamera foto masuk ke Hindia-Belanda, seorang juru potret Belanda bernama Van Kinsbergen memotret bangunan Candi Sewu yang masih utuh. Rupanya setelah pemotretan itu, terjadi gempa yang cukup dahsyat yang menyebabkan candi induk runtuh. Orang-orang Eropa yang gemar mengarsip itu rupanya memiliki keingintahuan dan hasrat untuk membuat candi itu utuh kembali. Akhirnya, dilakukan lah penelitian dan penggalian sampai ditemukan banyak arca dan kemudian dilakukan lah pemugaran. Tentu berdasarkan dengan data kumpulan mereka, arsip mereka, yang mereka buat dengan perspektif mereka. Lagi-lagi, ini tidak salah bagi mereka, namun entah apakah itu benar bagi si bangunan candi itu sendiri.
Saat Jepang datang ke bumi Jawa, hingga revolusi fisik akibat agresi militer Belanda, tidak terdapat catatan tentang pemugaran candi. Catatan tentangnya baru ada setelah kemerdekaan di tahun 1980-an. Kali ini, orang Indonesia sendiri yang memugar. Dengan data yang dikumpulkannya sendiri, dengan arsip yang diolah sendiri, dan dengan perspektif sendiri.
Banyaknya pergantian kekuasaan membuat Candi Sewu mempunyai banyak sekali pengalaman. Setiap pengalaman memberi tandanya masing-masing; menambahkan, mengurangi, memotong, meniban, ataupun menggabungkannya dengan elemen lain. Ia menjadi suatu kolase, hasil karya benturan dan timpalan kebudayaan yang berlangsung berabad-abad lamanya.
Maka, kebingunganku dengan cara berpikir kebudayaan Hindu-Buddha sangatlah wajar, mengingat kami mempunyai perbedaan umur yang sangat jauh, dan mengalami hal yang sangat berbeda. Aku lahir di akhir abad kedua puluh. Kesamaan antara Candi Sewu dan aku adalah kami berdua mengalami masa orde baru. Bedanya, ia mengalami langsung dengan dipugarnya Candi Sewu di tahun 1980-an. Sedangkan aku, aku mengalami akhir masa orde baru dengan termediasi. Aku mendengar cerita-cerita heroik tentang aksi mahasiswa dari kakakku yang sudah kuliah. Dua bulan sebelum aku masuk SD, aku menonton peristiwa lengsernya Suharto lewat televisi. Candi Sewu dan aku juga sama-sama mengalami pergantian abad menuju abad kedua puluh satu. Milenium baru. Aku mengalami bertumbuhnya kaum menengah di Indonesia sejak kondisi perekonomi negara meningkat pesat. Aku juga mengalami waktu pertama kali Indonesia mengadakan pemilihan umum, dengan kandidat yang bukan dari kalangan elit. Walaupun presiden silih berganti, pemugaran, perbaikan, dan perawatan dialami terus-menerus oleh Candi Sewu. Semakin banyak batu yang terkikis waktu, dan semakin banyak batu pengganti yang ditambahkan.
Aku juga mengalami bertumbuhnya teknologi media yang membuat perputaran arus informasi bergerak lebih cepat dari kedipan mata. Ini tentu membuat saling silang budaya semakin kompleks. Tubuhku yang berdarah Jawa tapi lahir dan besar di Jakarta ini mengalami disorientasi. Modernitas telah masuk ke dalam cara hidup orang-orang pendahuluku, membuat aku berpikir dan merasa dengan cara yang modernistik; tidak tradisional, tidak juga modern. Kolase di kepalaku dari hasil melihat dan mengalami banyak peristiwa menjadi berlapis-lapis, sehingga mencari akar menjadi hal yang mustahil.
Kemudian di tahun 2021, tubuhku, tubuh generasi milenial ini, hadir di antara puing-puing tersebut. Tubuhku yang hadir menyentuh dan berusaha menggeser dan mengangkat yasti, menambah elemen baru di situ. Persentuhan antara tanganku dan yasti, serta kakiku yang bersisian dengannya, juga dorongan bahuku ke arah yasti, membuat bentuk-bentuk baru yang belum ada sebelumnya. Kehadiranku yang memakai baju berwarna dominan biru di antara batu-batu andesit berwarna hitam keabuan, serta warna kulitku yang cokelat ditimpa sinar matahari dan bayangan-bayangan candi perwara menambahkan ornamen baru dalam kanvas lukisan Candi Sewu. Tubuhku pun, yang baru tersentuh kebudayaan selama nyaris tiga puluh tahun, berhimpitan dengan tubuh yang sudah dijatuhi kebudayaan beribu tahun lamanya. Sehingga, kolase tubuhku yang digabungkan dengan kolase candi menjadikan suatu kolase baru. Kolase yang mencoba terus bertahan di tengah terpaan arus modernitas, yang dipaksa untuk menjadi turis dengan harus menjadi serba cepat dan memaknai banyak hal hanya dengan kulitnya, namun juga tetap mencoba memaknai sejarah peradabannya. Sehingga hal itu akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam memaknai hidup.
[1] http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/arsitektur-candi-sewu/